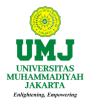Sejak dekade silam, para muslimah di Indonesia gencar diberi ilmu-ilmu kewanitaan Islam. Utamanya tentang perempuan harus menutup aurat, menuntut ilmu, dan mengembangkan potensi diri karena perempuanlah yang akan mendidik generasi penerus agama dan bangsa.
Sekarangpun kita masih melihat dan merasakan gencarnya pendidikan tersebut. Kita melihat tempat-tempat menuntut ilmu—sekolah, pengajian, dan forum lainnya—banyak dipenuhi oleh wanita. Rumah diurus oleh wanita, anak diurus oleh wanita, bahkan lapangan kerja mulai banyak diisi oleh wanita. Memang benar bahwa belum semua wanita memperoleh pendidikan, tetapi para pewaris Kartini kita sudah bangkit. Sudah banyak gerakan perubahan yang diinisiasi oleh wanita, baik dari yang muda hingga yang paruh baya.
Namun, tantangan zaman senantiasa berubah. Ibu sudah kuat, tetapi ia tidak bisa sendiri. Ibu menguat, tapi ayah malah berkurang kekuatannya.
Konon, negara kita mengalami krisis figur ayah. Indonesia bahkan disebut berada di peringkat ketiga dalam kategori “negara tanpa ayah”. Ayah hadir secara fisik, tetapi tidak hadir dalam hati keluarga. Peran ayah direduksi jadi sebatas pemberi nafkah, membuatnya “tidak terlalu” berjasa dibanding peran ibu. Anak memiliki ayah, tetapi kehilangan figur ayah. Inilah yang dimaksud sebagai fatherless.
Masyarakat kita tengah merasakan betapa ketidakhadiran ayah (dalam pengasuhan) berdampak pada pengembangan diri anak. Mengutip hasil penelitian dan berbagai survei, 75% penghuni lapas yang divonis seumur hidup tidak mendapatkan kasih sayang ayah. Sebanyak 92% pengedar narkoba tumbuh besar tanpa melihat peran ayah. Sebesar 65% pelaku bunuh diri dan 60% pelaku tindak korupsi serta 78% pelaku pemerkosaan tidak didampingi figur ayah.
Anak yang tidak memiliki figur ayah akan mencari kasih sayang dari laki-laki yang lain. Teman perempuan saya yang mengalami ini, mencoba mengisi kekosongan ayahnya dengan mencari laki-laki lain: pacar, bahkan sugar daddy. Teman laki-laki saya yang tidak mendapat kasih sayang ayah cenderung bersikap feminin. Anak-anak seperti teman saya ini, sebagian beruntung menemukan figur laki-laki teladan dalam perjalanan hidupnya. Namun, yang sebagian lagi kurang beruntung dan berakhir menjadi pecinta lelaki.
Perlu diingat, “ayah” berbeda dengan “figur ayah”. Anak yatim masih bisa tumbuh dengan baik karena ia memiliki figur laki-laki pengganti ayahnya: kakek, paman, kakak laki-laki, atau guru. Namun, anak tidak harus yatim untuk kehilangan figur ayah. Fenomena ayah yang ada tapi tiada inilah yang perlu diberi perhatian khusus.
Meskipun memberi nafkah juga merupakan amal yang mulia, sejatinya ayah berhak mendapatkan peran yang lebih berarti lagi. Anak belajar cara mengambil keputusan, kepemimpinan, dan keteguhan pada prinsip dari ayahnya. Anak juga memperoleh rasa aman dan kepercayaan diri dari sosok ayahnya.
Dalam sebuah sesi seminar bersama pasutri konselor pernikahan, Dandiah Consultant, disampaikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki maskulinitas dan femininitas. Kita kerap berpikir laki-laki tidak boleh feminin dan perempuan tidak boleh maskulin, tapi setiap orang ternyata butuh keduanya. Idealnya, laki-laki memiliki 75% maskulinitas dan 25% femininitas, sementara perempuan memiliki 75% femininitas dan 25% maskulinitas.
Anak belajar menumbuhkan sisi femininitasnya dari figur ibu. Sisi ini meliputi cinta yang lembut (tender love), sosok perasa (feeler), pelindung, pendukung, pemberi afeksi, pemberi maaf, dan penjaga kedamaian/keharmonisan.
Sisi maskulinitas dipelajari anak dari figur ayahnya. Sisi ini meliputi cinta yang keras (tough love), sosok pemikir rasional (thinker), penantang (challenger), juga menjadi penentu kemandirian, menumbuhkan penghargaan diri, dan rasa tanggung jawab.
Setiap anak sudah memiliki fitrah cinta dan seksualitas, sisanya tergantung bagaimana orang tua menjaga agar fitrahnya tumbuh lurus dan optimal. Kalaupun fitrah ini tidak tumbuh dengan baik, manusia memiliki fitrah lain berupa fitrah perkembangan. Ia punya kemampuan untuk unlearn dan relearn. Ia bukan makhluk yang konstan dan pasif, yang tidak punya daya mengubah diri.
Fitrah perkembangan inilah yang menjadi semangat generasi masa kini untuk menyembuhkan ‘luka’ dan melunasi ‘utang’ pengasuhan dari orang tua. Berbagai upaya mereka lakukan agar tidak kembali menurunkan luka yang sama kepada anak-anaknya di masa depan. Termasuk di antara evaluasi ini adalah dimulainya gerakan untuk meningkatkan peran ayah di dalam keluarga.
Baru kita sadari belakangan ini bahwa ayah tidak cukup hanya memberi nafkah lahir. Manusia memiliki jasad, akal, dan ruh, yang menurut prinsip tawadzun (keseimbangan) ketiganya perlu dipenuhi kebutuhannya. Nafkah lahir dari ayah, yaitu sandang, pangan, papan, dan pendidikan, baru mencukupi kebutuhan jasad dan sebagian akal. Masih ada sisa kebutuhan akal dan ruh, yaitu berupa pembinaan dan keteladanan dalam kehidupan dan spiritualitas.
Mengenai pembinaan kehidupan dari ayah, umat ini telah sadar untuk men-tadabbur kembali kisah-kisah di dalam Al-Qur’an. Dari 17 kisah tentang dialog antara ayah dan anak di dalam Al-Qur’an, 14 di antaranya adalah dialog dengan ayah: Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Ya’qub dengan Nabi Yusuf, Luqman dengan anaknya, dan masih banyak lagi. Masuknya Luqman dalam jajaran tersebut juga memberi hikmah pada kita bahwa setiap ayah adalah da’i bagi anaknya. Ayah tidak harus jadi nabi untuk mendakwahi anak.
Ayah dalam kebudayaan kita adalah sosok perkasa tanpa perasaan, tetapi Rasulullah SAW memberi contoh yang sangat baik tentang hal ini. Diriwayatkan dalam berbagai hadits bahwa Rasul adalah sosok yang tidak malu menampakkan kasih sayang kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan: beliau mengungkapkan rasa sayang, mendoakan, bahkan mengecup anak-cucunya. Akhlak seperti ini juga baik diterapkan kepada istri. “Istri yang bahagia akan membuat suasana rumah dan lingkungan pengasuhan menjadi lebih bahagia,” demikian satu dari banyak ilmu yang dibagikan oleh gerakan ayah pembelajar, Fatherman.id.
Umat sudah menyadari bahwa Indonesia krisis figur ayah. Karena itulah, umat sedang giat dan perlu lebih gencar dalam mendidik laki-laki. Sudah banyak guru agama yang mendalami bidang pernikahan dan pengasuhan yang memberikan ilmunya secara gratis lewat media sosial. Sebut saja Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Salim A. Fillah, Ustadz Abu Bassam Oemar Mita, juga Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri. Itu baru yang terkenal, masih banyak ustadz-ustadzah lainnya yang getol berdakwah di bidang ini.
Sudah banyak di kalangan orang tua, ajakan agar anak laki-laki dididik sama dengan anak perempuan—diajarkan memasak, bersih-bersih, dan bertanggung jawab atas urusan sendiri. Ibu-ibu pun didorong untuk memberi ruang belajar kepada ayah, untuk bersabar sejenak menghadapi ayah yang belum sekompeten ibu untuk mengembangkan diri dalam kemampuan mengasuh anak.
Dalam lingkungan pendidikan formal pun, para guru dan pengambil kebijakan diharapkan untuk tidak membiarkan begitu saja ketika siswa laki-laki ketinggalan berprestasi dari siswa perempuan. Masyarakat kita sudah cukup lama memaklumi ini dengan kalimat “Laki-laki memang begitu,” padahal bisa saja kalimat tersebut menghalangi laki-laki untuk menggapai potensi yang lebih besar. Kita percaya laki-laki diberi peran oleh Allah SWT sebagai pemimpin (qowwam), tetapi tidak berusaha memupuk sifat-sifat qowwam yang cemerlang sejak dini.
“Satu ayah lebih berharga daripada seratus guru sekolah,” demikian guratan penyair Inggris George Herbert. Seperti semangat untuk mendidik para ibu yang berbuah manis hari ini, semoga gerakan untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan memiliki dampak manis terhadap keutuhan keluarga, tumbuh kembang anak, dan terbentuknya generasi-generasi teladan penerus agama dan bangsa.