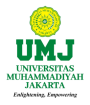Perhatian rakyat Indonesia saat ini sedang tertuju pada konflik agraria yang terjadi di Rempang yang warganya menolak direlokasi demi pembangunan Rempang Eco-City. Masyarakat Rempang telah mengetahui adanya rencana proyek ini sejak tahun 2007. Proyek ini melibatkan PT MEG Group Artha Graha milik Tommy Winata, serta investor dari Singapura dan Malaysia. PT MEG mendapatkan hak pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun.
Kemudian pada Juli 2023, Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di pulau Rempang, sebagai bagian dari konsep Rempang Eco-City dengan nilai proyek sebesar 11, 5 miliar USD.
Proyek yang diperkirakan mampu menarik investasi sebesar Rp 318 triliun dan masuk ke dalam Program Strategis Nasional ini akan menggusur 16 kampung tua yang berada di lingkungan proyek. Padahal, warga setempat telah tinggal secara turun-temurun di lokasi tersebut. Warga Rempang yang menolak rencana ini melakukan aksi demonstrasi di Kota Batam yang berujung terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan yang bertindak represif.
Apa yang terjadi di Rempang ini bukanlah yang pertama, namun sudah kesekian kalinya terjadi di Indonesia. Warga yang terdampak penggusuran dipaksa meninggalkan rumahnya, terkadang tanpa ada solusi yang jelas. Dalam kasus Rempang, tidak ada kejelasan perihal ganti rugi, hunian baru dan tempat relokasi, karena warga Rempang dianggap sebagai warga liar karena tidak memiliki sertifikat tanah.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, MH., menjelaskan konteks permasalahan yang terjadi dalam kasus Rempang. Ia menyoroti perlakuan Pemerintah yang melabeli warga Rempang sebagai warga liar karena tidak mempunyai sertifikat.
“Ada perbedaan pandangan antara Pemerintah dan BP Batam dengan warga, mereka menganggap bahwa masyarakat Rempang adalah warga liar karena tidak memiliki sertifikat. Sedangkan masyarakat berpandangan bahwa mereka bukanlah pendatang liar karena sudah lahir dan tumbuh di sana. Bahkan pada tahun 2019 di Rempang ada penyelenggaran Pemilu, yang artinya mereka tidak bisa dikatakan sebagai warga liar,” jelas Ibnu.
Pelabelan itu menjadi persoalan dasar yang memicu terjadinya konflik dengan warga. Menurutnya, jika melihat sejarah, sertifikat terbilang hal baru bagi Indonesia. Aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah dulunya diperoleh tanpa menggunakan sertifikat, misalnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hasil dari menasionalisasi perusahaan asing.
“Artinya Pemerintah melakukan tindakan formalistik terhadap warga negara. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada warga negara dengan memberikan sertifikat, bukan justru melakukan sebaliknya,” tambah Ibnu.
Dosen yang aktif di Perhimpunan Advokat Indonesia ini mengungkapkan bahwa hukum menyatakan segala macam tanah yang ada di Indonesia itu bukan milik Negara, tetapi Negara hanya diberikan hak kuasa. Pemilik yang sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. Hal itu termuat dalam aturan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). “Pemerintah tidak bisa melabeli setiap tanah sebagai milik negara, karena itu sudah usang warisan masa kolonial,” ungkap Ibnu.
Ibnu menjelaskan hak tentang masyarakat adat berada di atas hak negara menguasainya. Masyarakat adat perlu mendapat perhatian lebih oleh Pemerintah. Dalam kasus masyarakat Rempang, ada 16 Kampung Tua yang bisa dibuktikan asal-asulnya, tetapi pemerintah mengabaikannya.
Memurut Ibnu, masyarakat Rempang tidak bisa dikatan sebagai warga liar karena masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kasus masyarakat Rempang terjadi akibat tidak adanya perlindungan hukum atas tanah yang kemudian di cap sebagai warga liar. Namun, adanya perlindungan hukum tidak menjamin konflik dapat dicegah.
Ibnu menilai persoalan tersebut terjadi karena perlindungan hukum tentang pertanahan di Indonesia belum optimal. Kasus soal konflik pertanahan dapat menjerat siapapun. Tidak hanya menjerat warga yang tidak memiliki, tetapi yang juga mempunyai sertifikat.
Kasus Rempang mengingatkan kita bahwa sistem pertahanahan kita memungkinkan kejadian serupa terulang. Hal itu ditambah bergantungnya Pemerintah dalam jenis usaha ekstratif dengan melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa mempertimbangkan hak-hak warga negara khususnya masyarakat adat. “Ini mengakibatkan konflik horizontal antara pemerintah dan warga negara,” ucap Ibnu.
Ibnu berpendapat meningkatnya konflik agraria karena tanah merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. “Jika kita memiliki tanah maka otomatis akan memiliki kekuasaan, karena kita mempunyai alat produksi. Terlebih lagi, di masa mendatang ada tiga hal yang diperebutkan oleh negara-negara lain yakni tanah, pangan, dan energi,” ungkap Ibnu.
Terakhir, Ibnu menegaskan bahwa persoalan Rempang menjadi pelajaran untuk Masyarakat. Kendati, sertifikat tidak bisa menjamin, tetapi itu produk hukum yang mengikat. Masyarakat juga harus menyadari setiap aset yang dipunya harus memiliki jaminan hukumnya.
Tentunya negara juga harus mengubah pola pendekatan represif terhadap kasus konflik agraria. Negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Kalau tidak, maka akan terus terjadi pertumpahan darah atas warga negara kita sendiri.
Penulis : Fazri Maulana
Editor : Tria Patrianti