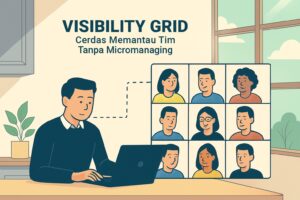Mudik bukan hanya sekadar tradisi tahunan di Indonesia, tetapi juga fenomena ekonomi besar yang membawa dampak luas bagi berbagai sektor. Setiap tahun, jutaan masyarakat melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman, menciptakan arus pergerakan manusia dan uang yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan RI, pada tahun 2024 jumlah pemudik diperkirakan mencapai 167,2 juta orang, sedangkan pada 2025 diproyeksikan sekitar 146,48 juta orang. Arus pergerakan ini meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik, terutama melalui konsumsi barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam infrastruktur transportasi, lingkungan, dan distribusi sumber daya.
Pendekatan ekonomi sirkular dan ekonomi Islam menawarkan solusi dalam mengelola mudik agar lebih produktif dan berkelanjutan. Ekonomi sirkular berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah, sedangkan ekonomi Islam menekankan keseimbangan dalam distribusi kekayaan serta keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Menggabungkan kedua konsep ini dapat menciptakan sistem mudik yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membangun ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Salah satu tantangan terbesar dalam mudik adalah tingginya konsumsi energi, terutama dari sektor transportasi. Lonjakan penggunaan kendaraan pribadi selama musim mudik menyebabkan kemacetan yang berujung pada meningkatnya konsumsi bahan bakar dan emisi karbon. Pada tahun 2023, arus kendaraan harian di Tol Jakarta-Cikampek mencapai 203 ribu unit per hari, angka yang kemungkinan besar meningkat pada tahun 2024 dan 2025 seiring bertambahnya jumlah pemudik. Jika rata-rata satu kendaraan menghabiskan 10 liter bahan bakar per hari, maka konsumsi bahan bakar pada puncak mudik bisa mencapai 2,03 juta liter per hari hanya di satu jalur tol utama. Dari perspektif ekonomi sirkular, ini adalah bentuk pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat dikurangi dengan optimalisasi transportasi massal berbasis energi bersih.
Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas angkutan umum, tetapi kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal masih rendah. Dalam ekonomi sirkular, strategi seperti insentif bagi pengguna transportasi umum, peningkatan fasilitas angkutan publik, dan penggunaan kendaraan listrik harus dipercepat. Jika setidaknya 20% dari pemudik beralih ke moda transportasi massal, maka konsumsi bahan bakar bisa ditekan hingga ratusan juta liter, yang berdampak pada pengurangan emisi karbon dan penghematan anggaran energi nasional.
Selain transportasi, konsumsi selama mudik juga perlu mendapat perhatian serius. Peningkatan konsumsi makanan dan minuman dalam kemasan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyumbang utama limbah selama periode mudik. Rest area, terminal, dan stasiun menjadi titik akumulasi sampah yang sulit dikelola. Jika setiap pemudik menghasilkan rata-rata 0,5 kg sampah per hari, maka dalam 10 hari periode mudik, total sampah yang dihasilkan bisa mencapai 73 juta kilogram atau setara dengan 7.300 truk sampah penuh. Dalam ekonomi sirkular, pengurangan limbah dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan, membawa wadah makanan dan botol minum sendiri, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jika 50% pemudik mengadopsi kebiasaan ini, maka sekitar 36 juta kilogram sampah bisa dicegah masuk ke tempat pembuangan akhir.
Namun, penerapan ekonomi sirkular saja tidak cukup. Pendekatan ekonomi Islam memberikan perspektif tambahan yang menekankan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Fenomena mudik yang mengalirkan dana dari kota ke desa bisa menjadi momentum redistribusi kekayaan yang lebih adil. Sayangnya, banyak transaksi selama mudik bersifat konsumtif dan tidak menghasilkan dampak jangka panjang bagi perekonomian daerah.
Jika konsep zakat dan infaq produktif diterapkan dalam tradisi mudik, dampaknya bisa jauh lebih besar. Sebagai ilustrasi, jika dari 146,48 juta pemudik pada tahun 2025, masing-masing menyisihkan Rp10.000 saja, maka dana yang terkumpul akan mencapai Rp1,464 triliun. Jika jumlah tersebut digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi desa, maka dampaknya bisa sangat signifikan. Misalnya, dengan rata-rata modal usaha mikro sebesar Rp5 juta, dana ini bisa digunakan untuk mendirikan 292.800 usaha kecil baru di desa-desa tujuan mudik. Jika setiap usaha menyerap setidaknya 2 tenaga kerja, maka lebih dari 585.600 orang bisa mendapatkan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran dan mencegah urbanisasi berlebihan pasca-Lebaran.
Tidak hanya itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial berbasis wakaf produktif, seperti sekolah, klinik kesehatan, atau pusat ekonomi berbasis komunitas. Dengan sistem pengelolaan yang baik, zakat dan infaq tidak hanya menjadi alat bantuan sementara, tetapi juga investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam, di mana harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan maslahat bagi orang lain.
Selain zakat, ekonomi Islam juga mengajarkan pentingnya konsumsi yang halal dan thayyib—bukan hanya dari segi kehalalan zat, tetapi juga dari dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Selama mudik, konsumsi makanan cepat saji dan produk-produk berbasis impor cenderung meningkat, sementara produk lokal sering kali kurang mendapat perhatian. Jika pemudik lebih banyak membeli produk lokal dari petani atau pengusaha kecil di daerah, maka efek pengganda ekonomi akan lebih besar.
Sebagai contoh, jika rata-rata pemudik membelanjakan Rp1 juta untuk oleh-oleh dan kebutuhan selama mudik, maka total transaksi bisa mencapai Rp146 triliun. Jika setidaknya 30% dari belanja tersebut dialokasikan untuk produk lokal, maka sekitar Rp43,8 triliun akan masuk ke ekonomi desa, memperkuat daya beli masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan usaha mikro. Hal ini lebih sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya ekonomi berbasis komunitas (al-iqtishad al-ijtima’i), di mana transaksi ekonomi dilakukan secara berkeadilan dan memberi manfaat bagi banyak orang.
Sinergi antara ekonomi sirkular dan ekonomi Islam dapat menjadi kunci dalam menciptakan mudik yang lebih produktif dan berkah. Jika ekonomi sirkular memberikan solusi dalam efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah, maka ekonomi Islam memastikan bahwa kekayaan yang beredar memberikan dampak sosial yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, mudik tidak hanya menjadi ajang perayaan dan perjalanan kembali ke kampung halaman, tetapi juga momentum untuk membangun ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam menerapkan kebijakan yang mendorong keberlanjutan dalam mudik. Insentif bagi pengguna transportasi umum, regulasi pengurangan sampah plastik, serta kampanye kesadaran tentang zakat dan infaq produktif harus digalakkan. Jika semua pihak bekerja sama, maka mudik tidak hanya menjadi pengalaman yang lebih nyaman dan efisien, tetapi juga menjadi salah satu instrumen perubahan ekonomi yang lebih luas.
Pada akhirnya, dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular dan ekonomi Islam secara bersamaan, mudik tidak hanya membawa kebahagiaan bagi individu dan keluarga, tetapi juga berkah bagi masyarakat luas serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Jika langkah ini diterapkan secara konsisten, maka tradisi mudik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat menjadi momentum transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(Tulisan ini pernah dimuat di halaman Republika)