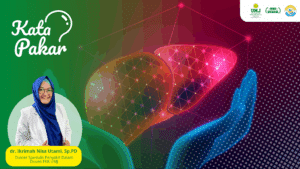Pada 16 Mei 2024, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi RUU usul inisiatif DPR. Hal ini memunculkan polemik di masyarakat karena perubahan tersebut terkesan hanya bagi-bagi kekuasaan dari Prabowo-Gibran ke partai pengusungnya untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH., menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait persoalan RUU Kementerian Negara.
Dekan FH ini mengatakan, harus melihat tingkat urgensinya jika ingin melakukan perubahan. Pasalnya, UU Kementerian Negara pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan sudah diketok sejak lama, yakni pada 2011. Menurutnya jika RUU tersebut disahkan saat ini, momentumnya kurang tepat karena bisa dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau perubahan itu berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MK di 2011 perihal kedudukan wakil menteri yang menjadi persoalan maka itu jelas urgensinya dan bisa dilakukan perubahan. Hal ini karena permohonannya dikabulkan MK walaupun hanya sebagian,” tuturnya saat diwawancarai di Ruang Dekan FH UMJ, Rabu (22/05/2024).
Dwi memandang jika memang ada urusan baru dengan tanggung jawab di kementerian baru maka itu adalah sebuah kebutuhan yang perlu dilakukan. Kendati demikian, penambahan kementerian harus hati-hati agar tidak menyebabkan tumpang tindih kewenangan.
“Misalnya kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Pemerintahan Desa (Pemdes) karena keduanya memiliki kewenangan terhadap pemerintah desa. Dalam hal ini, pemerintah pusat menegaskan jika urusan administrasi ada di Kemendagri dan pembinaannya di Pemdes, maka baiknya kewenangan tersebut dimiliki satu lembaga saja,” jelas Dwi.
Ia mengutarakan apabila keberadaan penambahan kementerian negara berdasarkan bagi-bagi kekuasaan, tentu itu tidak ada urgensinya. Kondisi yang saat ini terjadi mengarah kepada berbagi kekuasaan di kalangan partai pengusung presiden terpilih, bukan selayaknya pembagian kekuasaan untuk tugas pemerintahan.
“Jadi, kalau konteksnya benar-benar kebutuhan, baik atas dasar keputusan MK 2011 atau kebutuhan sebuah kementerian untuk mengurus urusan baru yang memang tadinya tidak ada dan harus ada maka itu sebuah urgensi. Namun, kalau untuk bagi-bagi kekuasaan adalah bukan suatu urgensi sehingga harus dilihat konteksnya dengan cermat,” ungkap Dwi.
Apabila perubahan terkait penambahan kementerian negara terealisasi, menurutnya otomatis akan berakibat terhadap keuangan negara. Adanya kementerian baru pasti membutuhkan pendanaan.
Dampak untuk keuangan negara tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama dari sisi regulasi, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu membutuhkan dana mulai dari pembahasan hingga keputusannya.
Kedua, perlu ada pembangunan lembaga untuk bekerja karena tidak mungkin menumpang di kantor kementerian yang lain. Ketiga, sumber daya manusia untuk mengisi kementerian yang baru. Kementerian tersebut pasti membutuhkan pegawai lewat perekrutan atau mengambil dari kementerian yang ada dan wajar pula jika ada pendanaan untuk gaji, tunjangan, dan sebagainya.
“Kalau banyak pengeluaran terhadap keuangan negara dari penambahan jumlah kementerian, pasti akan berdampak ke stabilitas nasional kehidupan bangsa,” ucap Dwi.
Dwi menekankan, presiden dan wakil presiden terpilih saat ini harus fokus ke janji kampanye, salah satunya makan siang dan susu gratis, serta pembangunan IKN yang masih berlanjut.
“Jangan sampai adanya penambahan kementerian mengorbankan anggaran lain, seperti wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk makan siang dan susu gratis. Oleh karena itu, presiden lebih baik memikirkan kebutuhan saat ini dengan memanfaatkan keuangan negara secara cermat dan benar,” ujarnya.
Ia berpesan kepada masyarakat, khususnya civitas academica agar bersikap netral dan kritis terhadap polemik RUU Kementerian Negara. Netral yang dimaksud, yaitu harus memahami bahwa penambahan atau pengurangan jumlah kementerian negara adalah hak prerogatif presiden.
“Presiden dianggap lebih tau kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi, kalau memang presiden dan negara membutuhkan, itu adalah haknya. Kita harus bijak karena presiden sudah menilai dan menentukan,” kata Dwi.
Menurutnya, sikap kritis dapat dilakukan dengan mengawasi dan memberikan masukan terhadap perubahan UU Kementerian Negara, sepanjang berkaitan dan mengkaji secara komprehensif keberadaan UU tersebut. Namun, apabila sudah terlanjur diketok palu maka dapat mengajukan judicial review ke MK.
Dwi mengimbau civitas academica dan masyarakat agar mengimplementasikan bentuk kritis tersebut melalui media sosial atau media massa. Pasalnya, jika dengan cara demontrasi saat ini cukup rawan dan riskan karena terkadang tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah justru merugikan pedemo.
“Jadi, kritis kita disampaikan dalam bentuk tulisan-tulisan di media. Jika sudah sangat melanggar, kita bergerak ke MK, tetapi jika hanya masukan saja, bisa lewat media. Ini lebih manjur dan aman untuk memberikan kritik ke pemerintah,” pungkasnya.
Penulis : Qithfirul Fahmi
Editor: Dinar Meidiana